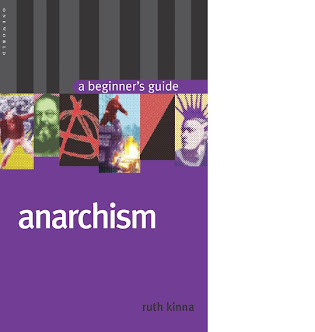KEPUTUSAN INDONESIA MENANDATANGANI CAFTA
KEPUTUSAN INDONESIA MENANDATANGANI CAFTA
(Perspektif International Soceity-Centric Constructivism)
Oleh
Heri Alfian
A. Pendahuluan
Berlakunya kesepakatan perdagangan bebas antara Cina-dengan negara-negara anggota ASEAN atau yang dikenal dengan China-ASEAN Free Trade Area atau CAFTA pada 1 Januari 2010 memunculkan beragam reaksi dari berbagai kalangan di Indonesia. Berbagai elemen masyarakat mulai dari masyarakat biasa, buruh pekerja industri, mahasiswa, akdemisi, tokoh masyarakat, pengamat ekonomi, pengusaha, sampai politisi berkomentar terhadap pemberlakuan kesepakatan tersebut. Komentar-komentar mereka terbelah ke dalam dua kubu yaitu kelompok yang mendukung pemberlakuan perdagangan CAFTA dan kelompok yang menolak. Kelompok pendukung berargumen seputar peluang dan keuntungan yang akan didapatkan oleh Indonesia dalam CAFTA yaitu potensi peningkatan ekspor Indonesia ke China yang sangat menjanjikan karena China memiliki penduduk 2 miliar orang lebih, yang menjadikannya pangsa pasar terbesar di dunia.
Sebaliknya, kelompok yang menolak menyatakan bahwa pemberlakuan CAFTA akan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia karena faktanya produk-produk Indonesia belum siap bersaing dengan produk-produk Cina. Industri Indonesia tidak akan mampu menyaingi produk-produk Cina yang sangat murah bahkan sebelum CAFTA diberlakukan yaitu 30 persen di bawah harga produk-produk Indonesia. Dapat dibayangkan bagaimana murahnya produk Cina setelah berlakunya CAFTA yang membebaskan tarif masuk barang-barang dari Cina menjadi nol persen. Dengan kemampuan daya beli masyarakat Indonesia yang tergolong masih rendah, maka kekhawatiran tersebut sangat masuk akal karena konsumen tentunya akan cenderung lebih memilih barang dengan harga lebih murah.
Penolakan terhadap CAFTA terus meluas karena berbagai dampak mulai dirasakan terutama oleh kalangan industri di mana banyak di antara mereka yang menutup usahanya karena tidak mampu bersaing. Sebagai gambaran dalam industri tekstil, pada 2009 hingga Juli, nilai ekspor industri ini sudah merosot sekitar 520 juta dolar Amerika Serikat. Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia juga menjerit. Sejak tahun 2000 ketika bea masuk masih diberlakukan, industri baja Indonesia terus mengalami defisit perdagangan karena kalah bersaing dengan produk impor. Defisit ini dipastikan membengkak, jika bea masuk jadi nol persen.
Kondisi-kondisi itu kemudian memunculkan tuntutan agar pemberlakukan CAFTA ditunda sampai Indonesia benar-benar siap menghadapi persaingan bebas dengan Cina. Atas berbagai reaksi tersebut, pemerintah berupaya bertahan atas kebijakan yang telah diambil dengan berargumen bahwa CAFTA adalah peluang besar dan merupakan momentum bagi Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi yang selama ini terjadi.
Dalam kajian politik luar negeri, fenomena di atas menarik untuk dikaji karena secara teoritis keputusan politik luar negeri adalah kepanjangan dari politik dalam negeri (foreign policy begins at home). Artinya keputusan politik luar negeri menjadi “hasil politik” yang menggambarkan pentingnya strategi politik untuk mencapai kesepakatan dengan situasi domestik untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan ketentuan teori ini maka setiap keputusan politik luar negeri seharusnya adalah perwujudan dari keinginan masyarakat negara tersebut, sehingga pelaksanaannyapun akan mendapatkan dukungan dari mereka.
Atas dasar itu maka fenomena penolakan CAFTA di Indonesia dapat dikatakan tidak sejalan dengan apa yang digariskan oleh teori politik luar negeri pada umumnya. Tulisan ini akan menjelaskan apa sebenarnya yang melatarbelakangi Indonesia menandatangani dan menerapkan CAFTA dan memberikan gambaran tentang logika pengambilan keputusan luar negei oleh suatu negara dengan menggunakan CAFTA sebagai ilustrasi. Untuk tujuan tersebut, tulisan ini menggunakan pendekatan international society-centric constructivism (ISC) yang dikemukakan oleh Martha Finnemore. Tulisan ini dibagi ke dalam lima bagian yaitu pertama, pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang urgensi permasalahan, kedua memberikan gambaran tentang CAFTA. Bagian ketiga menjelaskan teori ISC, bagian keempat menjelaskan tentang keputusan Indonesia menandatangani dan memberlakukan CAFTA, dan bagian ke lima adalah kesimpulan dari keseluruhan isi tulisan.
B. China-Asean Free Trade Area
Terbentuknya CAFTA diawali oleh sejarah hubungan yang tergolong baru antara Cina-Asean. Hubungan Cina dengan negara-negara anggota Asean sebagai sebuah grup baru terjalin pada tahun 1994 yang ditandai dengan exchange of letters antara Sekjen Asean dengan Perdana Menteri China pada tanggal 23 Juli 1994 di Bangkok. Dua tahun berikutnya Asean menerima Cina sebagai Full Dialog Partner pada pertemuan Asean Ministerial Meeting (AMM) ke-29 di Jakarta yang menandakan perubahan satus Cina dari Consultative Partner sejak tahun 1991. Satu tahun berikutnya, tepatnya pada bulan Desember 1997, Presiden Cina Jiang Zemin melakukan pertemuan informal untuk pertama kalinya dengan seluruh pemimpin Asean (Asean Plus One) dan membicarakan tentang hubungan kemitraan sebagai negara yang bertetangga dan saling percaya menyongsong abad ke-21.
Kedekatan Cina-Asean terus berlanjut tapi belum mebicarakan masalah pembentukan area perdagangan bebas. Isyu perdagangan bebas baru muncul ke permukaan ketika PM Cina Zhu Rongji mengajukan proposal kerja sama ASEAN-China pada ASEAN+China Summit pada bulan November 2001. Pertemuan itu kemudian mendasari terbentuknya ASEAN-China Expert Group yang kemudian berhasil menyusun sebuah laporan yang berjudul Forging Closer ASEAN-China Economic Relations in the Twenty- First Century. Laporan tersebut berisi empat poin penting yaitu:
a. Pendirian Area Perdagangan Bebas Asean-Cina dalam jangka waktu 10 tahun.
b. Penyediaan berbagai fasilitas perdagangan dan ivestasi.
c. Pemberian technical assistance dan capacity building bagi negara-negara ASEAN, khususnya bagi negara-negara anggota baru ASEAN (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam/ CLMV.
d. Perluasan kerja sama dalam berbagai bidang yaitu keuangan, pariwisata, pertanian, peningkatan sumber daya manusia, industri, hak kekayaan intelektual,usaha kecil dan menengah, lingkungan, kehutanan dan produk-produk hasil hutan, dan energi.
Tahun berikutnya, tepatnya pada Nopember 2002 negara-negara Cina dan negara-negara ASEAN mengesahkan ASEAN-China Framework Agreement on Economic Cooperation dalam KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja. Dua tahun kemudian tepatnya pada 29 Nopember 2004, CAFTA ditandatangani oleh menteri-menteri negara Asean dan China pada 2004. Di bawah perjanjian tersebut tarif barang-barang yang diperdagangkan di antara enam negara-negara ASEAN (ASEAN 6) dan Cina dikurangi sampai nol persen pada tahun 2010, sedangkan untuk negara-negara ASEAN lainnya (CLMV) akan berlaku pada tahun 2015. Adapun untuk barang-barang yang termasuk dalam Early Harvest Product (EHP) telah dimulai pada tahun 2004.
B. Pendekatan International Society-Centric Constructivism
Politik luar negeri menurut asumsi tradisional selalu merujuk pada “world of states” di mana negara-negara adalah aktor utama dan mereka berlomba-lomba untuk meraih kepentingan nasional masing-masing yaitu upaya meraih kedaulatan dan kemerdekaan. Intinya secara sadar setiap kebijakan luar negeri ditujukan untuk meraih kepentingan nasional atas dasar prinsip memaksimalkan keuntungan dan menekan kerugian seminimal mungkin. Pada prinsipnya politik luar negeri berjalan pada logika untung rugi (cost-benefit logic), yang dikenal dengan politik luar negeri realisme.
Pada kenyataannya, tidak semua dan bahkan seringkali negara mengambil atau melakukan politik/kebijakan luar negeri tanpa didasarkan pada prinsip di atas. Negara-negara berkembang misalnya mengambil kebijakan luar negeri yang seringkali tidak didasarkan pada kepentingan nasionalnya, namun lebih disebabkan oleh tekanan dan tuntutan lingkungan internasional baik itu negara lain maupun organisasi-organisasi internasional.
Kenyataan itu memperlihatkan bahwa negara pada dasarnya adalah suatu entitas yang tidak mengetahui apa kepentingan dirinya. Negara seringkali bingung tentang apa yang seharusnya dilakukanya, sehingga seringkali negara membuat/melakukan suatu kebijakan yang meniru negara lain. Dalam bentuk lain ketidaktahuan itu diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang tidak merujuk pada kepentingan masyarakatnya (domestik), atau juga dalam bentuk kebijakan yang seringkali berubah-ubah tanpa tujuan yang jelas. Beberapa pendekatan di dalam studi hubungan internasional seperti neorealisme dan konstruktivis international (international society-centric constructivism) berusaha menjelaskan tentang fenomena itu. Menurut neorealis, di dalam sistem internasional negara hanya melakukan apa yang digariskan oleh sistem. Negara tidak bisa berbuat apa-apa untuk merubah sistem internasional yang anarki. Negara berada pada posisi pasif dan hanya dapat melakukan adaptasi atas lingkungan internasional.
Adapun menurut konstruktivis yang dikemukakan oleh Martha Finnemore (sociological institutionalism), kepentingan negara ditentukan oleh struktur sosial /norma internasional (international social/normative structure). Struktur sosial/norma utama internasional yang berlaku dominan pada suatu masa tertentu merupakan strukutur mendasar yang menjadi prinsip utama di dalam proses sosialisasi (the socializing principle) yang terjadi di dalam sistem internasional. Menurut Finnemore norma utama yang dominan di dalam sistem internasional pada dasarnya didefinisikan menjadi tiga yaitu bureaucracy, human quality, dan market. Bureaucracy merupakan norma yang berhubungan dengan otoritas, sedangkan human quality adalah norma yang menyangkut penghargaan terhadap hak asasi manusia dan menginginkan kesetaraan bagi semua manusia dalam bidang politik dan ekonomi. Market adalah norma yang merujuk pada cara yang paling sah (legitimate) untuk mengatur aspek ekonomi.
Logika berpikir ISC menyatakan bahwa negara berada pada posisi adaptif di mana kebijakan yang dilakukan oleh negara adalah bentuk dari ketundukannya terhadap norma internasional terutama salah satu dari ketiga norma di atas. Dengan kata lain norma internasional menentukan bentuk perilaku seperti apa yang harus diikuti oleh negara. Norma itu kemudian menentukan identitas negara, di mana perubahan identitas akan mengikuti perubahan yang terjadi pada norma internasional yang berkembang. Selanjutnya identitas tersebut akan menentukan kepentingan negara di mana kepentingan dalam hal ini lebih berorientasi pada upaya untuk menunjukkan ‘ketaatan’ dan upaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan internasional.
Gambar 1. The Logic of International Society-Centric Constructivism
Sumber: dimodifikasi dari Martha Finnemore, dalam John M. Hobson, The State and International Relations, Cambridge University Press, UK, 2000, hal. 158.
Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa lingkungan internasional menjadi faktor yang menetukan apa yang harus dilakukan oleh negara. Perubahan tindakan negara yang diawali dengan perubahan identitasnya akan mengikuti perubahan yang terjadi norma internasional. Negara dalam konteks ini hanya berposisi sebagai normative-adaptive state. Adaptasi itu dilakukan dalam rangka penyesuaian dan bukan untuk memperbesar power dalam politik internasional. Logika ini juga disebut dengan the logic of appropriateness. Berdasarkan logika ini, keputusan politik luar negeri suatu negara tidak ditujukan untuk mencapai kepentingan nasional yang didasarkan pada aspirasi domestik, tetapi lebih pada upaya penyesuaian diri terhadap kondisi dan tuntutan lingkungan internasionalnya. Intinya adalah keputusan politik luar negeri lebih didasarkan pada upaya untuk mendaptkan “good image” yang selaras dengan negara-negara lain. Dapat dikatakan bahwa suatu keputusan politik luar negeri ditujukan agar suatu negara bisa menjadi bagian masyarakat internasional
Perubahan identitas dan kepentingan/kebijakan negara menurut Finnemore terjadi melalui teaching process yang dilakukan oleh organisasi internasional ataupun aktor-aktor non state, sehingga kebijakan negara tergantung pada apa yang “diajarkan” oleh organisasi internasional seperti Unesco, Bank Dunia, IMF, ICRC dan WTO. Prose situ dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 2. Teaching Process in International Society-Centric Constuctivism
T
Sumber: dimodifikasi dari Martha Finnemore, dalam John M. Hobson, The State and International Relations, Cambridge University Press, UK, 2000, hal. 150.
Teaching activities ini menurut Finnemore menyebabkan identitas negara-negara menjadi hampir sama dan itu berdampak pada kepentingan yang hampir seragam juga. Namun harus digarisbawahi bahwa Ia menolak adanya homogenisasi negara-negara karena pada dasarnya penyebaran struktur norma internasional tidak sama. Menurutnya, struktur norma internasional itu menyebar dari inti (core) ke batas terluar (periphery) sistem internasional. Penyebaran itu terjadi di dalam proses “teaching” terhadap negara-negara oleh organisasi internasional yang mulai dari bagian inti kemudian ke negara-negara pinggiran. Hal itu kemudian menyebabkan perbedaan tingkat penyerapan norma yang “diajarkan” kepada negara-negara. Satu hal yang dapat disepakati bahwa struktur utama dominan saat ini adalah norma pasar. Mengenai dampaknya terhadap negara-negara tentu secara faktual memang berbeda tingkat penyerapannya.
D. Keputusan Indonesia menandatangani China-Asean Free Trade Area
Keputusan Indonesia menandatangani dan memberlakukan CAFTA merupakan suatu keputusan politik luar negeri yang membawa konsekuensi bagi lingkugan domestik. Beberapa dari konsekuensi tersebut bersifat positif tetapi bisa juga negatif. Menurut pendekatan tradisional seperti teori decision making, kebijakan luar negeri adalah hasil pemilihan alternatif-alternatif yang tersedia, di mana pilihan yang didasarkan pada tujuan memperbesar keutungan dan dan meminimalisir kerugian. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap kebijakan luar negeri seyogyanya bertujuan untuk meraih tujuan (kepentingan nasional) semaksimal mungkin. Berdasarkan asumsi ini maka sepatutnya setiap pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara telah melalui proses menimbang dan mengukur baik buruk atau untung ruginya bagi kepentingan nasional.
Akan tetapi, pada kenyataannya, idealisme teoritis tersebut tidak selalu sesuai kenyataan. Banyak kasus keputusan politik luar negeri yang mendapat kritikan dan penolakan dari lingkungan domestik. Beberapa contoh yang terjadi di Indonesia misalnya, keputusan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengijinkan Singapura menggunakan beberapa wilayah Indonesia untuk melakukan latihan militer. Seperti diketahui, kebijakan tersebut merupakan hasil trade off antara Indonesia dengan Singapura, di mana Singapura akan menyetujui perjanjian ekstradisi dengan Indonesia dengan syarat Indonesia mengijinkannya melakukan latihan militer di wilayah Indonesia. Keputusan tersebut ternyata mendapat penolakan keras dari masyarakat. Masyrakat di berbagai wilayah melakukan demonstrasi memprotes kebijakan tersebut terutama dari daerah yang wilayahnya akan dijadikan medan latihan militer Singapura. Atas berbagai berbagai penolakan tersebut pemerintah akhirnya membatalkan perjanjian tersebut.
Pada tahun 2007, kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah kembali mendapatkan penolakan luas dari masyarakat. Kebijakan itu terkait dengan dukungan Indonesia terhadap resolusi PBB 1747 yang berisi sanksi terhadap Iran atas program nuklir yang dilakukannya. Banyak kalangan menilai, kebijakan pemerintah itu bertentangan dengan keinginan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menolak resolusi tersebut karena semata-mata merupakan hasil dari tekanan AS terhadap PBB. Mereka menilai bahwa dukungan atas resolusi tersebut sama saja dengan dukungan terhadap AS untuk menindas Iran, dan dalam spektrum yang lebih luas hal itu berarti dukunga terhadap penindasan dan penjajahan AS terhadap masyarakat muslim. Sebagai negara dengan mayoritas berpenduduk muslim maka kebijakan Indonesia tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi domestik yang ada.
Pada tahun 2010, keputusan Indonesia memberlakukan CAFTA juga mendapat protes dan penolakan luas dari berbagai elemen domestik, mulai dari kaum buruh industri, pengusaha, tokoh masyarakat, akademisi, politisi, dan bahkan pemerintah sendiri. Hal ini sangat mengherankan karena tentunya, sebelum kebijakan membuka perdagangan bebas dengan Cina (CAFTA), pemerintah telah mempertimbangakn kondisi lingkungan domestiknya. Berbagai penolakan yang muncul terhadap CAFTA didasarkan pada alasan bahwa Indonesia tidak atau belum siap bersaing dengan Cina. Produk-produk Cina yang sangat murah dan begitu massif dan selalu up to date tidak akan mampu disaingi oleh produk dalam negeri yang jauh lebih mahal dan lambat perkembangannya. Berbagai faktor mendasar yang melatarbelakangi ketidaksiapan tersebut adalah mulai dari pasokan energi terutama listrik yang tidak stabil dan pasokan bahan bakar minyak yang sering terganggu, tenaga kerja yang kurang terampil, sarana dan prasarana yang belum memadai terutama akses jalan, tingginya bunga pinjaman bank, pungutan liar, sampai pada kurangnya dukungan pemerintah termasuk birokrasi yang berbelit-belit dan lambat.
Pada titik ini maka hal penting yang harus dijawab adalah mengapa pemerintah mengambil kebijakan menyetujui dan meberlakukan CAFTA padahal kondisi domestik tidak memungkinkan? Apakah pemerintah tidak mengetahui kondisi-kondisi tersebut sehingga tidak menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan? Ataukan pemerintah mengetahui benar akan hak itu tetapi memang tidak dijadikan dasar pertimbangan yang penting? Bagian ini akan menjawab berbagai pertanyaan mendasar itu dengan menggunakan pendekatan international society-centric constructivism.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat tiga norma utama yang dominan di dalam sistem internasional yaitu bureaucracy, human quality, dan market. Jika merujuk pada kondisi saat ini dari ketiga norma tersebut, norma pasarlah yang paling dominan. Norma pasar seperti dikatakan oleh Finnemore merujuk pada pada cara yang paling sah (legitimate) untuk mengatur aspek ekonomi. Pasar menurut Robert Gilpin adalah:
as one in which goods and services are exchanged on the basis of relative prices; it is where transactions are negotiated and prices are determined. Its essence …is “the making of a price by haggling between buyers and sellers”.
Pada tingkatan yang lebih luas konsep pasar kemudian digunakan untuk menyebut berbagai bentuk pertukaran barang dan jasa di mana setiap individu memiliki kebebasan yang sama untuk bersaing di dalamnya, dan negara tidak boleh mencampuri atau mengintervensi mekanisme pasar yang diatur oleh penawaran dan permintaan.
Munculnya norma pasar berawal dari munculnya pemikiran kaum liberal yang berakar pada pemikiran Adam Smith. Smith megatakan bahwa kunci dari kekayaan dan power negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menurutnya ditentukan oleh pembagian kerja (division of labour) di mana hal itu sangat tergantung pada pasar. Atas dasar itu maka, jika suatu negara menjalankan kebijakan ekonomi merkantilisme yaitu menerapkan hambatan perdagangan atas barang dan perluasan pasar, maka negara tersebut telah mencegah kesejahteraan dan pertumbuhan ekonominya. Menurut David Ricardo, kesejahteraan negara dalam pandangan liberal akan didapatkan melalui apa yang disebut dengan comparative advantage yaitu keutungan yang diperoleh melalui spesialisasi yang dilakukan oleh negara pada produksi tertentu sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.
Sebagai sebuah norma, pasar yang dalam hal ini perdagangan bebas mengalami proses perkembangan pasang surut. Dinamika norma ini ditandai tidak hanya oleh dukungan tetapi juga kritikan dan pentangan terutama oleh negara-negara berkembang. Bagi negara berkembang sistem pasar dengan mekanisme perdagangan bebas adalah bentuk eksploitasi negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang. Berbagai penentangan itu misalnya dilakukan dalam bentuk upaya pemutusan hubungan dengan sistem perdagangan internasional, memaksa perubahan sistem, dan upaya pengintegrasian negara ke dalam rezim perdagangan yang ada. Akan tetapi, reaksi tersebut hanyalah riak kecil dalam perkembangan liberalisme beserta norma pasarnya, karena. Semakin lama norma itu semakin berkembang meskipun dengan berbagai penyesuaian seperti “diijinkannya” campur tangan pemerintah dalam pasar meskipun sangat terbatas. Pada awal dekade 1980-an hampir semua negara berkembang telah beralih ke ekonomi liberal yang berorientasi pada pasar, pencabutan intervensi, liberalisasi perdagangan dan investasi, dan privatisasi perusahaan negara.
Singkatnya, bentuk perekonomian dunia saat ini hampir sepenuhnya diatur oleh mekanisme penawaran dan permintaan. “Dogma” itu termanifestasikan pada perdagangan bebas yang telah mengglobal sedemikian rupa dan menyentuh hampir seluruh bagian dari dunia ini, di mana hampir tidak satupun negara yang tidak masuk dalam rezim perdagangan bebas. Francis Fukuyama bahkan mengatakan era saat ini sebagai kemenangan besar liberalisme dan menyebutnya sebagai the end of history.
Kemenangan liberalisme tersebut semakin dikuatkan oleh munculnya rezim perdagangan The General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) yang didirikan pada tahun 1948. Tujuan utama GATT adalah untuk menciptakan perdagangan internasional yang lebih bebas melalui pengurangan tarif dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan lainnya dan menciptakan regime atau aturan-aturan universal untuk melaksanakan commercial policy. Uruguay Round juga menetapkan tentang pemotongan tarif yang lebih besar, pengurangan yang signifikan dalam subsidi pertanian, penghilangan kuota tekstil lebih dari 10 tahun, atauran-aturan baru dalam services, intellectual property, trade related investment. Putaran ini juga merupakan asal mula dari terbentuknya organisasi World Trade Organization (WTO) yang merupakan bentuk baru (pengganti) dari GATT yang hanya berbentuk agreement. Sebagai suatu organisasi permanen, WTO telah memiliki struktur, aturan-aturan, dan prosedur-prosedur baru yang lebih komprehensif untuk mendukung tercapainya suatu rezim perdagangan internasional yang lebih bebas.
Beridirinya WTO ini kemudian mendorong lahirnya berbagai bentuk regionalisme ekonomi di hampir seluruh wilayah di berbagai belahan dunia. Regionalisme ekonomi merupakan suatu bentuk disain dan implementasi dari sekumpulan aturan/ kebijakan di dalam suatu kelompok negara-negara (region) yang bertujuan untuk mempermudah pertukaran barang di antara negara anggotanya. Berbagai organisasi ekonomi regional tersebut misalnya Uni Eropa (UE) yang didirikan pada tahun 1957, The Council of Arab Economic Unity/CAEU (1964), The Association of Southeast Asian Nations/ASEAN (1967), The Carribean Community and Common Market/CARICOM (1973), The Economic Community of West African States/ECOWAS (1975), The Latin American Integration Association/LAIA (1981), The South Asian Association for Regional Cooperation/SAARC (1985), The Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC (1989), dan The Southern African Development Community/SADC (1992).
Di kawasan Asia Timur khususnya negara-negara Asean, era regionalisme ekonomi dimulai pada tahun 1980-an yang dipengaruhi oleh meningkatnya integrasi produksi regional dan jaringan perdagangan. Peningkatan kedua hal itu telah mendekatkan hubungan negara-negara ASEAN dengan negara-negara tetanggannya yaitu Jepang, negara-negara Industri Baru di Asia timur atau yang dikenal sebagai EANIcs, China dan Vietnam. Era keterbukaan itu juga ditandai dengan pembentukan area perdagangan bebas Asean Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992 di dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas yang akan dicapai dalam waktu 15 tahun yaitu dalam kurun waktu antara 1993-2008. Ketentuan itu kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. ASEAN terus melakukan langkah internasionalisasi perdagangan dengan berpartisipasi aktif yan ditandai dengan munculnya upaya pembentukan East Asia Economic Group yang diusulkan oleh Perdana Menteri Malaysia Mahatir Mohammad pada tahun 1990. Keanggotaan EAEG akan mencakup seluruh negara Asia yang menjadi anggota APEC. Namun upaya ini tidak terlaksana karena munculnya konflik perdagangan AS-Jepang dan AS-Cina. Pada tabel berikut dapat dilihat perjanjian-perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan kerja sama ekonomi yang melibatkan negara-negara Asia Timur dan negara-negara Asean.
Tabel 1. The FTAs and Economics Partnership Agreement Involving East Asian and Southeast Asian Countries
Sumber: Puspa Delima Amri, New Issues in the WTO: Where does Indonesia Stand?, yang dikutip dari Kawai (2004).
Dalam dalam www.delidn.ec.europa.eu/en/.../relations_1_trade10_wtonewissues0702.pdf. Diakses 5 Juni 2010.
Note: The shaded cells indicate those arrangements within East Asia, that is, ASEAN+3, Hong Kong (China), and
Taiwan (China).
n.a.= not applicable.
a. Lao People’s Democratic Republic.
b. The Pacific-3 are Chile, New Zealand, and Singapore.
c. CER is the Australia and New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement.
d. EFTA is the European Free Trade Association (Iceland, Liechtenstein, and Switzerland).
e. Macao Special Administrative Region (China).
f. Mercosur is the Southern Cone Common Market (Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, and Venezuela).
g. ASEAN is the Association of Southeast Asian Nations.
Gelombang regionalisme dan kerja sama ekonomi yang menerpa kawasan tidak dapat dipungkiri menjadi faktor signifikan bagi Indonesia untuk melakukan hal serupa. Menurut catatan Amri pada tahun 2006 Indonesia sudah terlibat dalam sembilan perjanjian perdagangan (regionalisme) dengan berbagai negara. Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian-perjanjian tersebut menurut Amri sebenarnya tidak signifikan bagi perekonomian Indonesia, namun lebih dipicu oleh tren yang terjadi di kawasan Asia Timur dan khususnya negara-negara Asean. Contohnya adalah ketika Thailand melakukan negosiasi untuk menjalin kerja sama ekonomi dengan Jepang dan Cina, Indonesia juga melakukannya hanya semata untuk alasan mempertahankan eksistensi pasarnya di Jepang dan Cina.
Table 2: Preferential Trade Agreements Involving Indonesia
Sumber: Puspa Delima Amri, New Issues in the WTO: Where does Indonesia Stand?, yang dikutip dari www.depdag.go.id, Soesastro (2004), www.bilaterals.org, EFTA Secretariat Website hhtp://secretariat.efta.int.dalam www.delidn.ec.europa.eu/en/.../relations_1_trade10_wtonewissues0702.pdf. Diakses 5 Juni 2010.
Argumentasi bahwa keputusan Indonesia menandatangani CAFTA dilatarbelakangi oleh pengaruh norma internasional yang berkembang terbukti dari posisi neraca perdagangan Indonesia terhadap Cina yang terus mengalami defisit. Pada table di bawah ini dapat dilihat neraca pergangan Indonesia-Cina sebelum CAFTA diberlakukan.
Tabel 3. Neraca Perdagangan Indonesia-China, 1990-2009 (Ribu USD)
Tahun Total Ekspor Impor Neraca Perdagangan
1990 1486729 834385.8 652343.4 182042.4
1995 3236941 1741718 1495223 246494.5
2000 4789679 2767708 2021971 745736.6
2005 12505216 6662354 5842863 819491.3
2009 20074672 9055010 11019662 -1964652
Pertumbuhan (%)
1990-1995 16.8 15.9 18.0 6.2
1995-2000 8.2 9.7 6.2 24.8
2000-2005 21.2 19.2 23.6 21.2
2005-2009 12.6 7.9 17.1 -
1990-2009 - 13.4 16.0 -
Sumber: Dihitung dari Statistik Perdagangan Luar Negeri dalm Latif Adam, ACFTA Dalam Perspektif Hubungan Dagang Indonesia-China
http://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/03/19/acfta-dalam-perspektif-hubungan-dagang-indonesia-china. Diakses 5 Juni 2010.
Dari table tersebut dapat dilihat bahwa pada periode 1990-2009, pertumbuhan ekspor Indonesia ke China (7,9% per tahun) jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan impor Indonesia dari China (17,1 per tahun%). Ini menunjukkan bahwa kemampuan penetrasi produk China ke pasar Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan kemampuan penetrasi produk Indonesia ke pasar China.
Setelah empat bulan pelaksanaan, terbukti CAFTA menyebabkan defisit perdagangan Indonesia terhadap Cina. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan menuturkan selama empat bulan tahun 2010 ini, tercatat, hingga April besarnya defisit mencapai US$1,6 miliar. "April saja itu US$553,6 juta". Rusman menyebut, defisit itu terjadi karena nilai ekspor ke China lebih rendah dibanding impornya. Data BPS memperlihatkan, selama Januari-April 2010 jumlah ekspor RI ke China tercatat sebesar US$4,018 miliar, sedangkan nilai impornya mencapai US$5,61 miliar. Perdagangan itu lebih besar dibanding tahun lalu pada periode sama yang tercatat untuk ekspor sebesar US$2,274 miliar, sedangkan untuk impor sebesar US$3,794 miliar.
E. Kesimpulan
Ketentuan tarif masuk nol persen yang ditetapkan di dalam CAFTA dapat dipastikan akan menyebabkan pasar Indonesia akan semakin dibanjiri oleh produk-produk Cina. Kenyataan itu bisa dilihat di berbagai pasar besar maupun kecil di hampir seluruh Indonesia mulai dari kerajinan sederhana seperti anyaman bamboo, tusuk gigi. Mainan anak-anak, tekstil, meubel, garment, ponsel, sampai produk berteknologi tinggi seperti kendaaraan bermotor. Kondisi masyrakat Indonesia yang masih memiliki pendapatan rendah akan berakibat terupuruknya industri dalam negeri karena produk-produk yang dihasilkan lebih mahal dari produk Cina sehingga masyarakat tentunya akan lebih memilih produk murah.
Bagi pengusaha, murahnya harga produk Cina akan mendorong mereka untuk terus menambah impor karena tingginya permintaan sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Hal itu terbukti dari jumlah impor Indonesia dari Cina yang terus meningkat. Sebelum CAFTA diberlakukan secara penuh, pada periode 2003-2009, proporsi impor Indonesia dari China meningkat dari 8.8% menjadi 12,7%. Tidak mengherankan bila pada tahun 2009, China menduduki posisi kedua sebagai negara importir terbesar bagi Indonesia.
Dampak lanjutan yang akan ditimbulkan oleh kondisi tersebut adalah terjadinya deindustrialisasi dan meningkatnya pengangguran. Simulasi yang pernah dilakukan P2E-LIPI menunjukkan bahwa setiap penurunan kapasitas produksi sektor industri sebesar 10% berpotensi mendorong PHK (pengangguran) 500.000 orang. Betapa besarnya pengangguran yang akan muncul seandainya ACFTA menekan kapasitas produksi sektor industri sebesar 10% saja.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut kita mendapatkan gambaran bahwa keputusan Indonesia menandatangani dan memberlakukan AFTA lebih didasarkan pada upaya untuk memenuhi “tuntutan” lingkungan internasional yang dikuasai oleh norma pasar daripada untuk memenuhi kepentingan nasional. Pertanyaan sederhana yang dapat diajukan untuk menguatkan argumen tersebut adalah: apakah para pengambil kebijakan tidak mengetahui kondisi perekonomian dan dunia industri Indonesia? Sepertinya sangat sulit dipahami jika pemerintah tidak mengetahui hal itu sehingga tanpa pertimbangan memutuskan untuk menandatangani CAFTA.
DAFTAR PUSTAKA
Buku & Jurnal:
Biersteker,Thomas J., The “Triumph” of Liberal Economic Ideas in the Developing World, dalam Barbara Stallings, Global Change, Regional Response, The New International Context of Development, Cambridge University Press, USA, 1995.
Burchill, Scott and Andrew Linklater (eds), Theories of International Relations, ST. martin Press, N.Y., 1996.
Fukuyama, Francis, The End of History and the Last Man, Free Press, New York, 2006.
Gilpin, Robert, The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, New Jersey, 1987.
Gilpin, Robert and Jean MillisGilpin, Tantangan Kapitalisme Global Ekonomi Dunia Abad Ke-21, Murai Kencana, 2003.
Hobson, John M., The State and International Relations, Cambridge University Press, UK, 2000.
Kegley, Charles W. Jr. and Eugene R. Wittkopf, World Politics Trend and Transformations, Sixth Edition, St. Martin’s Press, New York, 1997.
Lim, Linda Y. C., Southeast Asia: Success Through International Oppeness, dalam Barbara Stallings (ed), Global Change, Regional Response, The New International Context of Development, , Cambridge University Press, USA, 1995.
Neack, Hey and Haney dikutip oleh Anak Agung Banyu Perwita, dalam Politik Luar Negeri Indonesia dan Dunia Muslim, Unpar Press, Bandung. 2007.
Ruggie,John Gerrad, Constructing the World Polity,Essays on International Institutionalization Routledge, New York, 1998.
Spero, Joan Edelman dan Jeffrey A. Hart, The Politics of International Economic Relations, Fifth Edition, St. Martin’s Press, New York, 1997.
Webber, Mark and Michael Smith, Foreign Policy in a Transformed World, Prentice Hall, United Kingdom, 2002.
Wyatt-Walter, Andrew, Regionalism, Globalization, and World Economic Order, dalam Louise Fawcett and Andrew Hurrel (ed), Regionalism in World Politics Regional Organization and International Order, Oxford University Press, New York, 1995.
Koran & Internet:
Chia Siow Yue, ASEAN-China Free Trade Area, Singapore Institute of International Affairs, Paper for presentation at the AEP Conference Hong Kong, 12-13 April 2004, dalam www.hiebs.hku.hk/aep/chia.pdf, diakses 3 Januari 2010.
Dialog antara Depperindag, Bea Cukai, Pelaku Usaha, dan Anggota DPR RI di TV One dengan pada 20 Maret 2010.
DR. Rusman Heriawan (Kepala Badan Pusat Statistik), Posisi Dagang Indonesia Kalah Atas China, dalam http://bisnis.vivanews.com/news/read/154679-posisi_dagang_ri_lemah_terhadap_china, diakses tanggal 5 Juni 2010.
Jusuf Kalla dalam dialog interaktif di TV One, 22 Januari 2010, pukul 20.30.
http://berita.liputan6.com/producer/201001/257719/Perdagangan.Bebas.dan.Ketergopohan.Kita. Diakses 10 Januari 2010.
Latif Adam, ACFTA Dalam Perspektif Hubungan Dagang Indonesia-China http://inspirasitabloid.wordpress.com/2010/03/19/acfta-dalam-perspektif-hubungan-dagang-indonesia-china. Diakses 5 Juni 2010.
Puspa Delima Amri, New Issues in the WTO: Where does Indonesia Stand, Dalam www.delidn.ec.europa.eu/en/.../relations_1_trade10_wtonewissues0702.pdf.
Sheng Lijun, China-ASEAN Free Trade Area: Origins, Developments and Strategic Motivations, ISEAS Working Paper: International Politics & Security Issues Series No. 1(2003), dalam www.iseas.edu.sg/ipsi12003.pdf, diakses 10 Januari 2010. Read more...